 |
| Roehana Koeddoes, pelopor pers perempuan Indonesia. (Foto: Ngopibareng.id) |
Koto Gadang, 20 Desember 1884. Seorang anak perempuan lahir dari pasangan Moehammad Rasjad Maharadja Soetan, seorang jaksa sekaligus wartawan, dan ibunya yang bernama Kiam. Tak ada yang tahu saat itu bahwa bayi yang diberi nama Roehana Koeddoes kelak akan melakukan tiga hal yang dianggap mustahil bagi perempuan pribumi di awal abad ke-20. Ia membuka sekolah ketika dirinya sendiri tak pernah duduk di bangku kelas. Ia menerbitkan surat kabar ketika perempuan dianggap tak pantas menulis. Ia menata rumahnya dengan perpustakaan dan jendela gaya Prancis yang membuat pejabat Belanda gempar.
Pada 17 Agustus 1972, di usia 87 tahun, ia berpulang. Namun 54 tahun setelah kepergiannya, namanya justru semakin keras diperbincangkan. Dalam diskusi “3 Wajah Roehana Koeddoes” yang digagas IDN TIMES, Meutya Hafid, Najwa Shihab, Irene Umar, Trini Tambu, Khairirah Lubis dan para pemimpin perempuan lainnya kembali menegaskan bahwa Roehana Koeddoes bukan sekadar jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Ia adalah arsitek kesadaran yang merancang bagaimana seharusnya perempuan berdiri di negerinya sendiri. Bukan dengan meminta izin. Tetapi dengan membuka pintu, mencetak huruf, dan meruntuhkan tembok tebal kolonialisme serta patriarki, bata demi bata, tanpa pernah gentar.
Wajah Pertama: Pendobrak Gerbang Pendidikan Perempuan
 |
| Cuplikan adegan Roehana Koeddoes memberikan pendidikan kepada perempuan di Koto Gadang. (Sumber: YouTube IDN Times) |
Minangkabau pada awal abad ke-20 adalah tanah yang kaya akan adat namun sangat tertutup bagi pendidikan perempuan. Kala itu, sekolah modern dianggap sebagai wilayah eksklusif laki-laki, sementara perempuan yang menuntut ilmu sering dipandang ganjil atau bahkan dianggap menyalahi kodrat. Roehana Koeddoes mengalami langsung getirnya diskriminasi tersebut. Meski terlahir sebagai putri seorang jaksa, ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk duduk di bangku sekolah formal. Namun, keterbatasan itu justru memicu semangatnya untuk belajar secara mandiri dari ayah dan saudara-saudaranya hingga ia berhasil menguasai huruf Latin, Arab Melayu, serta bahasa Belanda.
Kecerdasan yang ia miliki tidak pernah dinikmati sendiri. Sejak usia delapan tahun di Simpang Tonang, Roehana sudah menunjukkan dedikasinya dengan mengajar teman-teman sebayanya membaca dan menulis. Sebagaimana dicatat oleh Yati (2014), di tengah hierarki kolonial yang menempatkan perempuan pribumi di posisi paling rendah, seorang gadis kecil telah memulai sebuah perlawanan fundamental untuk memerdekakan kaumnya dari belenggu kebodohan.
Langkah besarnya semakin nyata pada 11 Februari 1911 saat ia menggagas berdirinya Vereeniging Karadjinan Amai Satia di Koto Gadang. Melalui organisasi ini, Roehana mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memajukan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan demi kemuliaan bangsa. Sejarah mencatat bahwa sekolah ini menjadi ruang belajar yang inklusif bagi semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga perempuan dewasa. Fitriyanti (2013) memaparkan bahwa Roehana juga menerapkan sistem iuran yang sangat solutif bagi mereka yang memiliki kendala ekonomi, di mana pembayaran dapat dicicil menggunakan hasil kerajinan tangan murid-muridnya.
Ekspansi perjuangannya berlanjut dengan pendirian Roehana School di Bukittinggi pada tahun 1917. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan keterampilan domestik seperti menjahit, tetapi juga membekali murid-muridnya dengan kemampuan baca tulis dan berhitung. Menurut Lbs et al., (2025), bagi Roehana, pendidikan adalah strategi perlawanan struktural untuk mengubah nasib kaum perempuan secara mendalam. Dari ruang kelas sederhana tersebut, ia membuktikan bahwa ketika sebuah pintu tidak pernah dibukakan untuknya, ia sanggup membangun pintunya sendiri demi membukakan jalan bagi ribuan perempuan lainnya.
 |
Diskusi “3 Wajah Roehana Koeddoes” dalam rangka Road to HPN 2026. (Foto: IDN Times) |
Dalam diskusi yang dilaporkan IDN TIMES, Jurnalis dan Pendiri Narasi, Najwa Shihab menegaskan bahwa Roehana adalah sosok istimewa karena keberaniannya membuka sekolah bagi perempuan di masa ketika akses pendidikan begitu sempit. Najwa juga memuji keberlanjutan Amai Setia yang masih berdiri hingga kini sebagai bukti bahwa pendidikan yang dirintis Roehana bukan sekadar proyek sesaat, melainkan fondasi pemberdayaan jangka panjang. Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Amai Setia, Trini Tambu, menyebutkan bahwa lembaga tersebut hingga kini terus memberdayakan perempuan melalui keterampilan dan literasi.
Dari ruang kelas sederhana tersebut, Roehana membuktikan bahwa ketika sebuah pintu tidak pernah dibukakan untuknya, ia sanggup membangun pintunya sendiri demi membukakan jalan bagi ribuan perempuan lainnya.
Wajah Kedua: Jurnalis Perempuan Pertama yang Menghidupkan Ruang Wacana
 |
| Halaman Soenting Melajoe (1912) . (foto: Wikimedia Commons) |
Pada 10 Juli 1912, terbitlah Soenting Melajoe di Kota Padang. Surat kabar ini bukan sekadar media biasa. Ia adalah surat kabar perempuan pertama di Hindia Belanda. Seluruh pengelolanya, dari pemimpin redaksi, editor, hingga penulis, adalah perempuan. Tiga kali seminggu, suara-suara yang selama ini hanya bergema di bilik Rumah Gadang, kini tercetak di atas kertas dan tersebar ke berbagai pelosok Sumatra bahkan hingga ke luar negeri.
Isinya bukan sekadar resep masakan atau tips merenda. Soenting Melajoe memuat artikel politik, gagasan kebangkitan perempuan, prosa, dan puisi. Di masa ketika pemerintah kolonial bahkan ragu memberi ruang bagi pribumi untuk berbicara, Roehana dan kawan-kawannya telah menciptakan ruang sendiri. Dalam kegelapan diskriminasi kolonial dan patriarki, Soenting Melajoe adalah mikrofon yang menyuarakan mereka yang selama ini tak terdengar (Samry & Omar, 2012).
Dalam diskusi “Wajah Roehana Koeddoes”, Pemimpin Redaksi IDN TIMES, Uni Lubis membacakan sebuah kutipan visioner milik Roehana yang maknanya tetap terasa relevan meski telah ditulis lebih dari satu abad silam. Roehana menuliskan, “Bangsaku, perempuan jadi pengarang. Rupanya amat banyak perempuan di berbagai pelosok yang bisa mengarang dan telah mengirimkan karyanya kepada kami serta mendukung pergerakan kami.” Melalui kalimat tersebut, Roehana menunjukkan kebanggaannya terhadap kemajuan kaum perempuan yang mulai berani bersuara dan berkontribusi secara intelektual bagi pergerakan mereka.
Tapi kemajuan tak pernah tanpa cemooh. Roehana dan rekan-rekannya dituduh melawan takdir. Dikatakan bahwa perempuan tidak sepatutnya menulis apalagi berbicara di ruang publik. Jawaban mereka tercatat dalam sejarah, tegas dan penuh martabat.
Roehana pernah menjawab cemoohan itu dengan tegas, “Kemajuan zaman tidak akan membuat kaum perempuan menyamai kaum laki-laki. Perempuan tetap perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang berubah adalah perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Tidak untuk ditakut-takuti, dibodoh-bodohi, apalagi dianiaya.” (Kutipan tersebut kembali dibacakan oleh Uni Lubis dalam diskusi 3 Wajah Roehana Koeddoes Perempuan Jurnalis Pertama di Indonesia yang ditayangkan di kanal YouTube IDN Times).
Di masa ketika hierarki kolonial menempatkan laki laki Eropa di puncak, lalu perempuan Eropa, lalu laki laki pribumi, dan di dasar sekali adalah perempuan pribumi, Soenting Melajoe adalah pemberontakan yang tercetak rapi. Ia bukan sekadar koran. Ia adalah ruang diskursif pertama yang diciptakan oleh dan untuk perempuan pribumi. Di ruang itu, mereka tidak hanya belajar membaca. Mereka belajar berpendapat, menolak, mengkritik, dan bermimpi tentang kemerdekaan.
Wajah Ketiga: Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Patriarki
Perlawanan Roehana Koeddoes tidak selalu bergelora di atas panggung politik. Ia bekerja lebih halus, tetapi menusuk langsung ke akar kuasa kolonial. Ia tidak mengangkat senjata, tetapi ia menguasai bahasa penjajah. Ia tidak merobohkan gedung pemerintahan, tetapi ia membangun rumah yang membuat pejabat Belanda gempar.
Di rumahnya di Koto Gadang, dinding dinding tidak lagi hanya papan kayu biasa. Sebuah rumah bergaya Eropa dengan empat jendela gaya Prancis berdiri, memadukan arsitektur kolonial dengan rumah gadang. Pejabat Belanda datang dan melihat sendiri. Seorang perempuan pribumi berani membangun rumah yang menyaingi kemegahan rumah pejabat Hindia Belanda. Di ruang tamunya, lemari kaca berisi buku buku berbahasa Belanda, Arab, dan Melayu. Rak pendek penuh tumpukan koran dalam dan luar negeri. Di sisi lain, tergantung selembar kain tenun halus buatan tangan perempuan Amai Setia. Perpaduan Timur dan Barat dalam satu ruang yang oleh tokoh dalam novel Belenggu Emas disebut sebagai “ruang tamu yang sarat peradaban” (Rahmayati, 2021).
Lebih dari itu, Roehana fasih berbahasa Belanda. Ketika menyambut tamu asing, ia berkata dengan lantang, tanpa ragu, tanpa gugup. “Ik ben Roehana Koeddoes. Welkom op de ambachtsschool genaamd Amai Setia.” Ia menggunakan bahasa penjajah, tetapi untuk memperkenalkan sekolahnya, karyanya, perlawanannya. Ia tidak kehilangan identitasnya. Kain ikat berwarna kesumba tetap melingkar di kepalanya. Tas rotan tersampir di bahunya. Ia adalah diri sendiri, tetapi ia menguasai dunia mereka.
Inilah strategi perlawanan yang cerdas. Roehana menguasai budaya penjajah, tetapi menggunakannya untuk meruntuhkan hegemoni mereka. Ia menunjukkan bahwa pribumi, apalagi perempuan pribumi, tidak inferior. Bahkan unggul. Era Politik Etis membuka sedikit celah pendidikan bagi pribumi, tetapi Roehana tidak menunggu celah itu melebar. Ia membuat pintu sendiri.
Perlawanannya simbolik, tetapi hasilnya nyata. Sekolah yang didirikannya masih berdiri hingga kini. Surat kabar yang dipimpinnya menjadi catatan sejarah pergerakan perempuan. Generasi demi generasi perempuan lahir dari benih yang ia tanam. Ia menantang struktur kolonial tanpa pernah melepaskan kain ikat di kepalanya.
Di ujung usianya yang 87 tahun, Roehana Koeddoes boleh saja berpulang pada 17 Agustus 1972. Tapi ia tidak pernah benar benar pergi. Sekolah Amai Setia masih mengajarkan perempuan menjahit dan membaca. Soenting Melajoe telah menjadi ruh yang menitis pada setiap media yang memberi ruang bagi suara perempuan. Dan rumahnya dengan jendela gaya Prancis itu adalah metafora yang abadi. Bahwa seorang perempuan Minangkabau tidak pernah kehilangan dirinya, bahkan ketika ia merangkul dunia. Bahwa identitas bukanlah tembok yang membatasi, melainkan akar yang membuatnya kokoh berdiri.
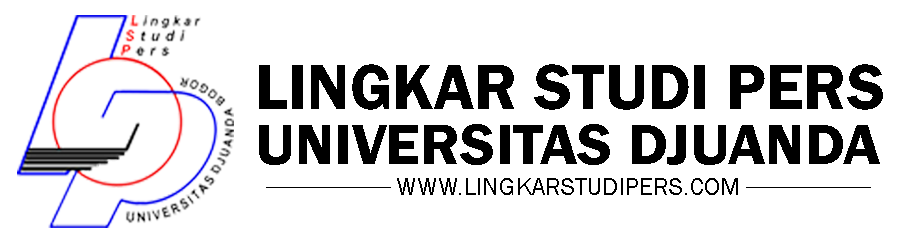


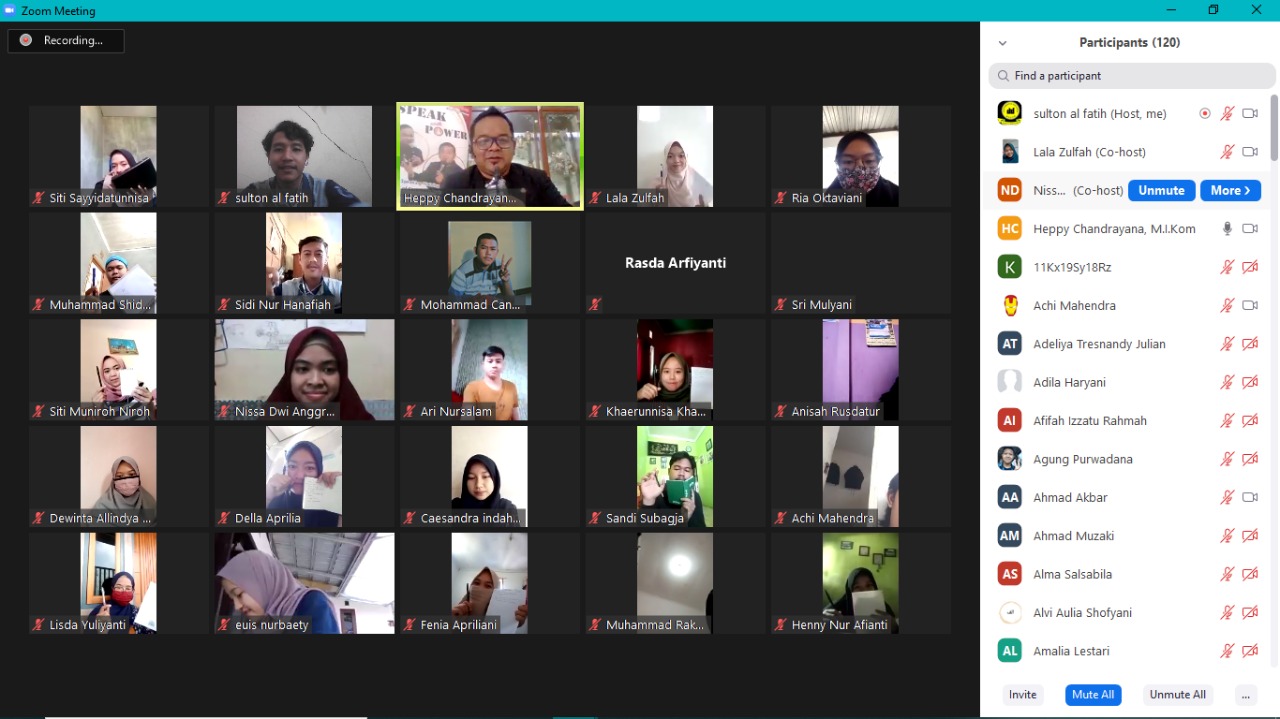











0 Komentar