 |
| Foto: IG @dzakyakram__, diakses 24 Juli 2025 |
Lingkar Studi Pers – Bogor, Setelah bertahun-tahun dikenal dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kini provinsi di ujung barat Indonesia itu resmi cukup disebut sebagai “Aceh”. Perubahan ini bukan sekadar penyederhanaan administratif, melainkan mencerminkan dinamika sejarah, budaya, dan politik yang telah membentuk identitas Aceh selama beberapa dekade terakhir. Meski terasa sederhana, penghapusan nama “Nanggroe Aceh Darussalam” menyimpan cerita panjang tentang perjuangan otonomi dan jati diri masyarakat Aceh. Nama “Aceh” mulai digunakan secara resmi sejak pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang disahkan pada 1 Agustus 2006 dan diundangkan pada 4 Agustus 2006. Undang-undang ini lahir sebagai hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Salah satu poin penting dalam UUPA adalah pengakuan terhadap kekhususan Aceh dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam hal penyebutan nama provinsi.
Sebelum UUPA berlaku, istilah “Nanggroe Aceh Darussalam” mulai dikenal luas setelah reformasi, tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memberikan status otonomi khusus kepada Aceh. Nama tersebut dipilih karena mengandung unsur budaya lokal yang kuat — “Nanggroe” berarti negeri, sementara “Darussalam” berarti negeri yang damai. Bagi masyarakat Aceh, nama ini sempat menjadi simbol perjuangan identitas daerah pascakonflik berkepanjangan yang menimpa provinsi tersebut. Seiring berjalannya waktu, penyebutan “Nanggroe Aceh Darussalam” secara perlahan mulai ditinggalkan dalam administrasi pemerintahan dan dokumen negara. Penggunaan nama “Aceh” dirasa lebih ringkas dan mudah diterapkan dalam sistem birokrasi nasional, namun tetap tidak mengurangi substansi kekhususan daerah yang telah dijamin melalui UUPA. Secara hukum dan formal, sejak 2006 hingga kini, nama resmi yang digunakan dalam semua surat keputusan, dokumen, dan keperluan pemerintahan adalah “Aceh”.
Meski demikian, jejak nama NAD masih melekat di hati sebagian masyarakat. Dalam konteks budaya, sejarah, dan bahkan nama-nama lembaga lokal, istilah tersebut tetap digunakan sebagai bentuk penghormatan terhadap masa lalu. Perubahan nama menjadi “Aceh” mencerminkan penyesuaian zaman tanpa menghapus jati diri, serta menjadi bukti bahwa sejarah dan identitas bisa tetap hidup, meski telah mengalami transformasi secara administratif. Perubahan nama dari Nanggroe Aceh Darussalam menjadi “Aceh” pada akhirnya bukan hanya tentang huruf dan kata, melainkan tentang bagaimana sebuah daerah mendefinisikan dirinya di tengah perjalanan sejarah yang panjang. Ia menjadi cermin bahwa identitas dapat beradaptasi, tanpa kehilangan akar yang mengikatnya. Dan Aceh, dengan segala keistimewaannya, akan tetap menjadi bagian penting dari mozaik kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam.
Penulis: Khalil Al
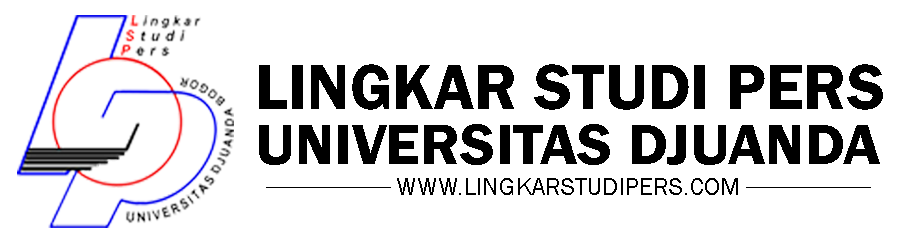


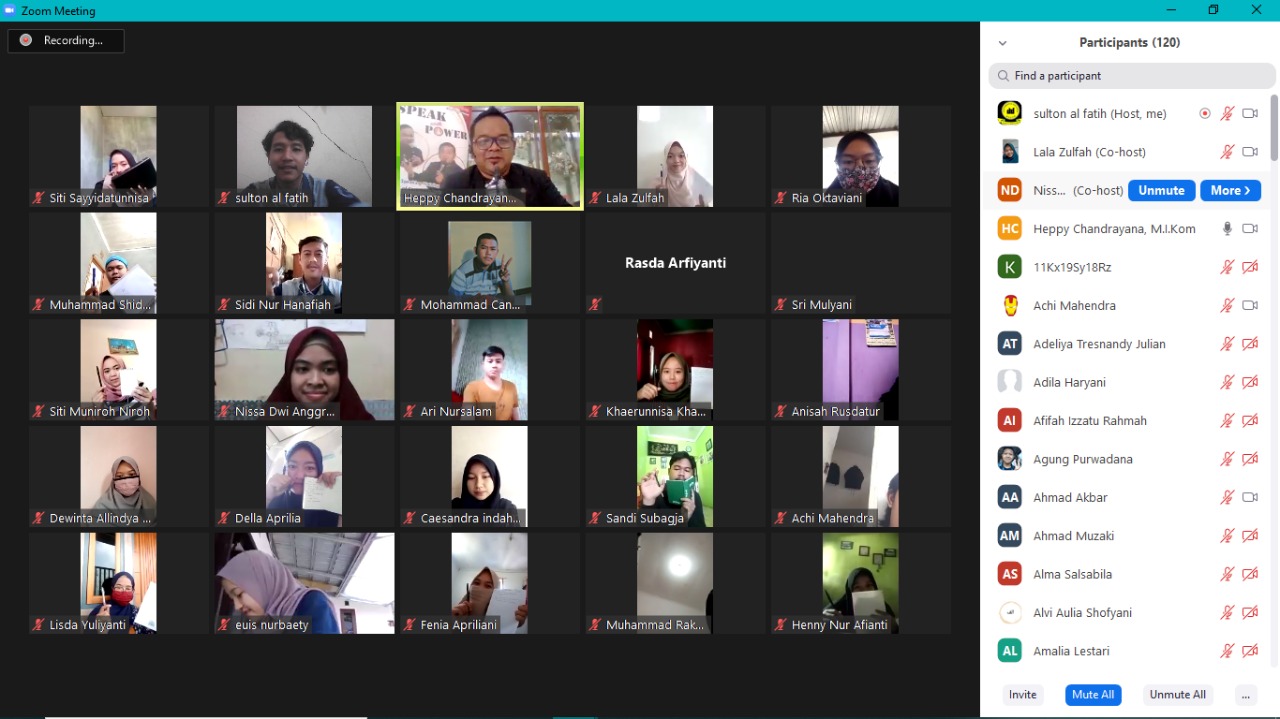











0 Komentar