 |
| (Nur Fatia Ramadhan Adinata - Mahasiswa Sains Komunikasi Universitas Djuanda Bogor) |
Lingkar Studi Pers, Bogor - Di setiap rezim dan zaman, jurnalis kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Mereka dipandang sebagai penjaga kebenaran, penyampai informasi kepada publik, sekaligus pengawas terhadap kekuasaan pemerintah. Tanpa jurnalis yang independen, demokrasi hanya akan menjadi kalimat kosong yang indah untuk diucapkan, tetapi rapuh dalam kenyataan.
Namun di era digital saat ini, peran jurnalis kembali dipertanyakan. Apakah mereka masih benar-benar menjadi pilar demokrasi? atau justru mulai bergeser menjadi ancaman informasi?
Tekanan digital telah mengubah wajah jurnalisme. Jika dulu standar utama adalah kedalaman dan ketepatan berita, kini kecepatan justru menjadi ukuran utama. Berita siapa yang tayang lebih cepat, dialah yang dianggap pemenang. Sayangnya, kecepatan sering kali mengorbankan kebenaran. Akibatnya, publik justru disuguhi berita yang bias, kekeliruan akan fakta, atau bahkan informasi yang menyesatkan.
Fenomena ini diperparah dengan logika klik. Banyak media lebih peduli pada judul yang bombastis ketimbang isi berita yang akurat. Alih-alih menjaga kualitas informasi, media malah terjebak pada perburuan trafik. Di titik inilah, jurnalis bisa berubah fungsi, dari pilar demokrasi, menjadi ancaman bagi publik yang membutuhkan informasi yang benar.
Kurt Lewin, seorang psikolog sosial, pernah memperkenalkan teori gatekeeping pada 1947. Teori ini menjelaskan bagaimana redaktur berperan sebagai “penjaga gerbang” informasi, menyaring, memilih, dan memutuskan berita mana yang layak sampai ke pembaca. Namun kini, gatekeeping tidak lagi sepenuhnya berada di tangan redaksi. Algoritma media sosial, tren viral, dan selera pembaca ikut menentukan apa yang muncul di layar kita. Ironisnya, media justru kerap mengikuti arus itu demi eksistensi.
Akibatnya, fungsi jurnalis sebagai filter kebenaran mulai melemah. Sebagian media tidak lagi memberi arah, melainkan memperkuat sensasi. Dan di titik itulah, demokrasi ikut terancam, karena masyarakat mulai kehilangan pijakan akan informasi yang kokoh untuk mengambil keputusan.
Apakah ini berarti jurnalis sepenuhnya menjadi ancaman? Tentu tidak. Masih ada ruang di mana jurnalis membuktikan diri sebagai pilar demokrasi. Kita melihatnya ketika mereka mengungkap kasus korupsi, menyuarakan kelompok yang terpinggirkan, atau memberikan kritik tajam pada kebijakan publik. Media lokal, seperti Metro Bogor, misalnya, masih berupaya menjaga kualitas gatekeeping dengan memilih berita berdasarkan kedekatan, dampak sosial, dan kelayakan publikasi.
Contoh-contoh seperti ini membuktikan, jurnalisme bermartabat masih mungkin bertahan, meskipun badai digital terus menghantam. Pertanyaannya adalah, apakah jurnalis hari ini akan terus berdiri sebagai pilar demokrasi, atau perlahan bergeser menjadi ancaman informasi?
Jawabannya kembali pada pilihan etis para pelaku media itu sendiri. Jika jurnalis tunduk pada logika pasar dan algoritma, tentu mereka akan kehilangan rohnya. Tetapi jika mereka tetap berpegang pada integritas, akurasi, dan keberanian, maka jurnalis akan tetap menjadi tiang penyangga demokrasi yang tak tergantikan.
Demokrasi membutuhkan jurnalis yang berani melawan arus, yang tidak tunduk pada sensasi, dan yang teguh berdiri di sisi kebenaran.
Tanpa itu semua, kita hanya akan hidup dalam kebisingan informasi tetapi kehilangan kebenaran yang seharusnya menjadi landasan bagi demokrasi.
Penulis: Nur Fatia Ramadhan Adinata
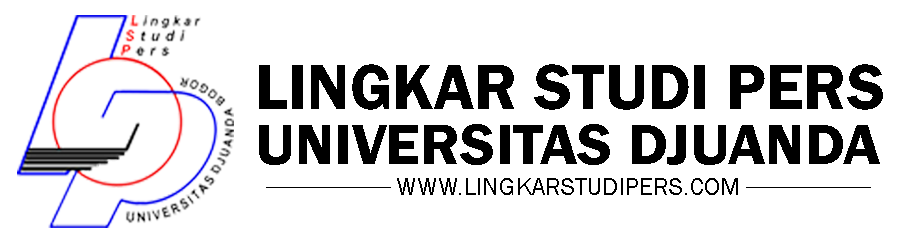


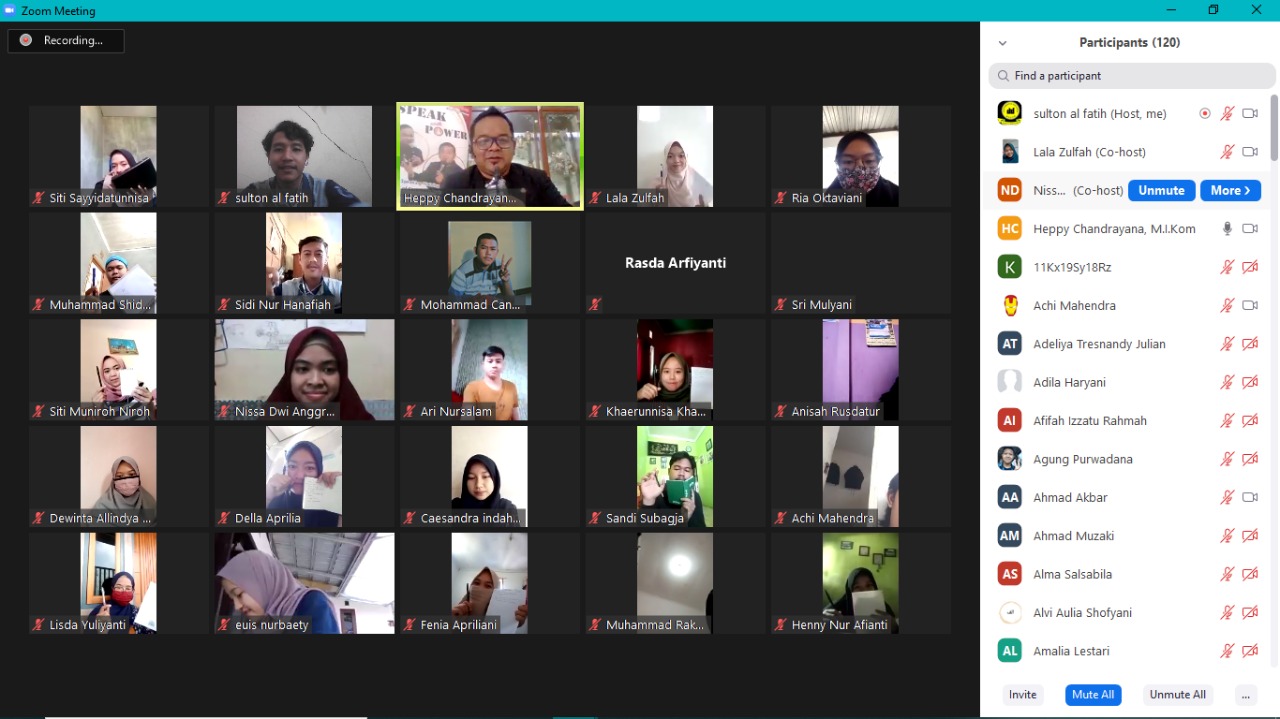











0 Komentar